Mengapa Kekerasan Terus Diingat? Bedah Buku Memori-Memori Kekerasan di Malang
Reporter
Anggara Sudiongko
Editor
A Yahya
17 - Feb - 2026, 08:04
JATIMTIMES – Sejarah Indonesia tidak pernah benar-benar steril dari kekerasan. Dari masa kolonial, revolusi, hingga periode reformasi, jejak luka itu membekas dalam ingatan kolektif masyarakat. Buku Memori-Memori Kekerasan: Ketegangan, Identitas, dan Nasionalisme hadir bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk mengajak publik merefleksikan masa lalu agar kekerasan tidak lagi dianggap sebagai solusi.
Bincang buku ini terselenggara di Kafe Pustaka Jalan Pekalongan No.1 Kota Malang Senin malam, (16/2/2026), melalui kolaborasi para penyusun buku bersama Komunitas Pelangi Sastra Malang, Marjin Kiri, Griya Buku Pelangi, dan Kafe Pustaka. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka yang membahas bagaimana ingatan atas kekerasan bekerja dalam kehidupan sosial hari ini.

Editor buku, Grace T Leksana, mengakui bahwa meneliti memori bukan perkara mudah. Dalam banyak disiplin ilmu, memori kerap dianggap abstrak, tidak pasti, bahkan dipertanyakan relevansinya.
Baca Juga : Tuai Sorotan Usai Pengakuan dr. Piprim Dipecat Menkes, Apa Itu Kolegium dan Apa Fungsinya?
“Memori sering dinilai kabur. Orang bertanya, ini meneliti apa sebenarnya? Masih kontekstual atau tidak?” ujarnya dalam diskusi.
Menurut Grace, gagasan buku ini berawal dari riset kolaboratif yang dilakukan bersama sejumlah peneliti. Salah satu pijakan awalnya adalah penelitian lapangan yang dilakukan oleh Arif Subekti dan tim. Namun, seiring proses berjalan, semakin banyak akademisi yang memiliki perhatian serupa terhadap isu memori kekerasan.
Alih-alih menjadikannya capaian individual, para penyusun memilih menjadikannya gerakan intelektual kolektif. Ilmu, kata Grace, bukanlah kisah penemuan tunggal seperti Newton menemukan gravitasi, melainkan hasil dialog panjang banyak pihak.
Buku ini membentangkan beragam peristiwa, mulai dari kekerasan era kolonial, tragedi 1948, hingga peristiwa pembunuhan dukun santet pada 1990-an. Meski rentang waktunya berbeda, seluruh peristiwa itu dinilai masih memengaruhi cara masyarakat Indonesia hidup hari ini.
“Meneliti memori bukan hanya menggali masa lalu, tetapi melihat bagaimana ingatan itu membentuk situasi kita sekarang,” tegasnya.
Pertanyaan tentang relevansi memori kekerasan juga mengemuka. Di ruang publik, suara seperti yang dialami Sumarsih dalam Aksi Kamisan kerap muncul. Ada yang mempertanyakan, mengapa terus mengingat peristiwa lama, mengapa tidak move on.
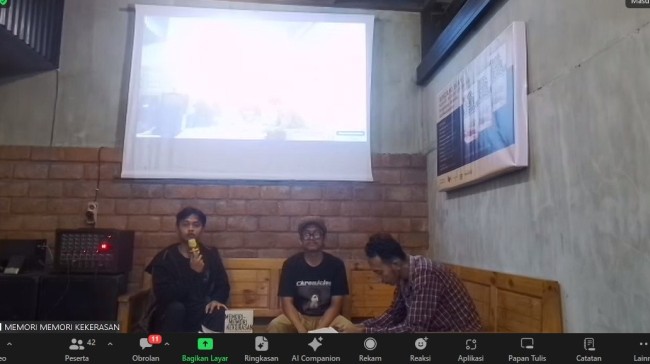
Penulis buku dan peneliti Arif Subekti menjelaskan bahwa fokus buku ini bukan semata pada peristiwa, melainkan pada cara masyarakat mengingat peristiwa tersebut.
Dalam penelitian lapangan di Blitar, Nganjuk, dan Kediri pada pertengahan 2021, ia bersama tim menelusuri kekerasan terhadap etnis Tionghoa pada masa revolusi. Mereka melakukan wawancara dan kunjungan situs untuk memahami bagaimana narasi kekerasan diwariskan atau justru dibungkam.
“Mengingat kekerasan memang traumatik. Tetapi justru dari situ terlihat polanya. Ada ingatan yang dilawan, ada yang disubordinasikan, ada yang diwariskan ke generasi muda,” ujar Arif.
Ia mencontohkan bagaimana komunitas berbeda dapat mengingat satu peristiwa dengan cara berbeda. Ingatan bukan sekadar fakta, melainkan narasi yang hidup, dipengaruhi posisi sosial, politik, dan identitas.
Penulis buku, Nurhafid Zulkarnain menambahkan, kesulitan terbesar sering kali datang dari narasumber sendiri. Trauma membuat saksi atau pelaku enggan menceritakan detail kejadian.
Dalam penelitiannya tentang relasi militer dan warga Tionghoa pada masa revolusi, ia menemukan arsip yang sangat terbatas. Banyak referensi justru berasal dari surat kabar berbahasa Belanda atau media Melayu dengan orientasi tertentu. Perspektif korban kerap tersisih dari dokumen resmi.
Baca Juga : Lulusan Terbukti Unggul, MA Wathaniyah Islamiyah Perpanjang MoU dengan STIE Malangkucecwara
Keterbatasan biaya dan akses juga menjadi tantangan tersendiri. Proses penelitian memori menuntut perjalanan, pertemuan tatap muka, dan waktu panjang membangun kepercayaan.

Penulis lain, Ana Mariana, menggarisbawahi pentingnya empati dalam menulis historiografi berbasis memori, terutama terkait kekerasan seksual.
Menurutnya, peneliti harus mampu menciptakan ruang aman agar korban merasa terlindungi ketika menceritakan pengalaman traumatis. Objektivitas bukan berarti menjaga jarak dingin, melainkan menghadirkan kepercayaan agar suara korban dapat muncul tanpa tekanan.
“Kita harus membangun konektivitas dan rasa aman. Tanpa itu, memori tidak akan terbuka,” ujarnya.
Ia menilai historiografi Indonesia masih minim dalam membahas kekerasan seksual secara mendalam. Banyak pola kekerasan berulang, namun belum seluruhnya tercatat secara utuh dalam sejarah resmi.

Perspektif lain datang dari penulis dan peneliti Belanda, Fridus Steijlen, yang menulis tentang memori kekerasan terkait Republik Maluku Selatan (RMS) dan diaspora Maluku di Belanda.
Ia menemukan bahwa orang Maluku di Belanda dan di Maluku memiliki hubungan kekeluargaan yang kuat, tetapi memori tentang RMS kerap menjadi topik yang dihindari. Diamnya pembicaraan itu menciptakan jarak emosional, seperti awan gelap yang menggantung di atas relasi mereka.
Menurut Fridus, membicarakan memori sensitif memang berisiko, apalagi terkait isu separatisme. Karena itu, peneliti harus membangun relasi kepercayaan yang kuat agar narasumber merasa aman.
“Jika tidak dibicarakan, dampaknya tetap ada. Justru karena itu perlu ditulis dan didiskusikan,” pungkasnya.
Buku Memori Memori Kekerasan menawarkan cara pandang baru terhadap sejarah. Bukan sekadar kronologi peristiwa, tetapi bagaimana ingatan dibentuk, diwariskan, dibungkam, atau diperebutkan.
Mengingat kekerasan bukan berarti memelihara dendam. Justru dengan memahami bagaimana memori bekerja, masyarakat dapat memutus logika yang membenarkan kekerasan sebagai jalan keluar persoalan.
Terlebih lagi, ditengah polarisasi identitas dan menguatnya nasionalisme sempit, refleksi atas memori kekerasan menjadi relevan. Sebab sejarah yang tidak dipahami secara kritis berisiko terulang dalam bentuk yang berbeda.














